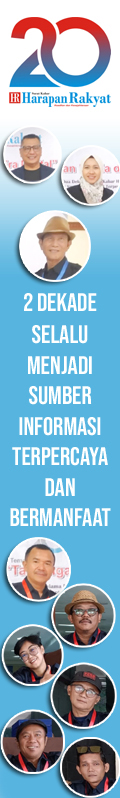Oleh: Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi
Artikel Opini Kompas tanggal 2 Agustus 2017 berjudul “Demokrasi Pancasila Itu” tulisan Sdr. Sabam Leo Batubara memanggil ingatan penulis tentang demokrasi yang diterapkan pak Harto segar kembali. Secara kebetulan penulis sewaktu berpangkat mayor hingga mayor jenderal menangani urusan perpolitikan nasional di Staf Sospol ABRI, DPR, Dephankam dan Mabes TNI-AD. Sehingga, tidak terlalu sulit untuk membandingkan tata kelola negara saat itu dengan setelah reformasi, yang pada intinya berakibat pada sistem kenegaraan yang amburadul serta dampaknya pada hiruk pikuk perpolitikan nasional, karena tidak ada rujukan yang logis, konsisten dan apalagi sistemik.
 |
| Saurip Kadi |
Secara substansial, demokrasi Pancasila dalam arti sebuah sitem kenegaraan lengkap dengan tata kelolanya yang didasari oleh keseluruhan nilai-nilai luhur Pancasila belum pernah dirumuskan oleh “Founding Father” kita, dan juga generasi penerusnya. Kondisi tersebut membuat tidak sedikit UU yang isinya tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.
Maka menjadi wajar kalau diumurnya yang ke 72 tahun, tata kehidupan bangsa dan negara kita, dirasakan makin menjauh dari niat, tekad dan cita-cita luhur yang mengantar berdirinya NKRI.
Pelajaran Berharga Masa Lalu
Orba dengan komitmen untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, kemudian menyatukan bangsa dengan menempatkan komunisme dengan PKI sebagai musuh bersama. Namun dalam prakteknya, Orba justru menggunakan “tool” yang lazim diterapkan di negara komunis.
Di negara komunis rakyat dibelah menjadi dua, bagi yang berpolitik hanya ada 1 partai yaitu Partai Komunis. Rakyat yang tidak berpolitik diawasi oleh Polit Biro Partai Komunis. Dan di negara komunis dikenal adanya lembaga skreening ideologi dan politik yang juga diperankan oleh Polit Biro Partai Komunis.
Selama Orba, rakyat kita juga dibelah menjadi dua. Bagi yang berpolitik hanya ada satu Partai yaitu Partai Orba dengan 3 nama, yaitu PPP, Golkar, dan PDI, dan ketiganya wajib dalam satu wadah yaitu Orba. Dalam Orba juga dikenal lembaga skrening ideologi dan politik yang diperankan oleh ABRI. Dan dengan kewenangan yang SAH, ABRI dalam hal ini khususnya TNI-AD juga melakukan kontrol sosial terlebih terhadap rakyat yang kritis, tidak sejalan dan apalagi yang menentang Orba.
Dan masih banyak lagi peran penting lainnya yang membuat ABRI dengan konsep Dwi Fungsi nya diperankan layaknya Polit Biro Partai Komunis dalam negara komunis, disamping tugas pokoknya dibidang Hankam.
Namun kalau mau jujur, sesungguhnya ABRI dimasa Orba hanyalah alat kekuasaan Pak Harto semata. Dan itulah kehebatan pak Harto yang mampu menjungkir balikan ilmu tata-negara yang secara universal dianut lebih dari 200 negara. Dan secara tidak sadar dalam hal tata kelola negara, para ahli kita dan masyarakat luas Indonesia dikelabuhi hingga tidak bisa lagi membedakan salah dan benar, sebagaimana yang sering diungkap almarhum Gus Dur: “minyak babi diberi cap minyak zaetun menjadi hahal”.
Dan masih banyak lagi tata kelola kekuasaan negara dibidang politik, ekonomi dan juga sosial lainnya yang menggunakan model dari ideologi lain, namun di cap Pancasila.
Kesemrawutan Demokrasi
Seperti dalam negara otoriter, UUD 1945 yang asli juga tidak memilah atau memisah antara negara dan Pemerintah, sehingga kelemahan Pemerintah otomatis sama dengan kelemahan negara. Hasil amandemen juga belum mengatur pemisahan atau pemilahan termaksud, dan menjadi tambah semrawut ketika norma dasar demokrasi yang menempatkan Kepala Negara sebagai lembaga tertinggi negara yang dilengkapi dengan sejumlah hak progratif antara lain dalam menyelamatkan musibah kemanusiaan, juga belum diaturnya. Hal tersebut membuat rakyat Porong Sidoarjo sempat merasakan seolah tidak ada negara, karena negara tidak hadir saat mereka tertimpa musibah kemanusiaan akibat kasus lumpur Lapindo.
Sistem presidensial kemudian begitu saja dicampur dengan sistem parlementer, tanpa menghitung dampak yang bakal ditimbulkannya. Ketika Presiden dipilih langsung melalui Pemilu, DPR nya bukan sebagai wakil rakyat, tapi wakil Partai. Lantas, rumus darimana azas “chek and balance” akan bisa terwujud.
Memang betul hasil amandemen telah mengatur keberadaan Partai dan Pemilu, tapi rumusan yang ada belum dikaitkan dengan pilihan sistem demokrasi. Padahal keberadaan Partai maupun Pemilu dalam sistem Parlementer jauh berbeda dan bahkan berseberangan dengan keberadaan Partai maupun Pemilu dalam sistem Presidensial.
Begitu pula struktur kenegaraan, yang semula sama persis dengan struktur negara komunis dalam hal ini ex USSR dengan tambahan 1 lembaga tinggi negara versi konstitusi Hindia Belanda yaitu DPA, kemudian diubah dengan mengganti UD/UG dengan DPD dan menghapus lembaga DPA. Namun, keberadaan DPD dan juga MPR tanpa kejelasan konsep politik yang hendak diwujudkan, padahal biaya politiknya harus ditanggung rakyat, setidaknya dalam hal anggaran.
Dan masih banyak lagi kesemrawutan dibidang politik dan juga bidang lainnya yang akhirnya melahirkan praktek oligharki dan kartel kekuasaan dan ekonomi. Praktek- praktek mafia terjadi disemua aspek kehidupan, termasuk juga dijajaran lembaga peradilan. Belum lagi bobroknya moral sebagian elit bangsa dan rusaknya birokrasi pemerintahan yang ditandai dengan maraknya korupsi berjamaah.
Tata Ulang Demokrasi
Warisan belenggu dan pasungan realitas yang begitu kuat sebagaimana gambaran diatas, oleh Presiden Jokowi kini sedang didobrak. Dengan sekuat tenaga yang bengkok diluruskan, yang salah dibetulkan dan yang merusak negara dihentikan. Dan agar kelak presiden berikutnya tidak kembali menerapkan cara-cara lama, maka kita perlu mendorong agar Presiden Jokowi bisa memberi warisan yang mulia kepada generasi penerus bangsa, berupa sistem kenegaraan yang betul-betul dilandasi nilai-nilai Pancasila, melalui amandemen UUD 1945 yang kelima.
Karena demokrasi adalah produk peradaban, maka kedepan sistem kenegaraan kita haruslah dilandasi nilai-nilai universal, termasuk ciri dan azas serta norma-norma dasar demokrasi yang kebenarannya telah dibuktikan dibanyak negara. Bangsa ini juga harus mempunyai ketegasan dalam menentukan pilihan demokrasi, apakah model presidensial, parlementer atau sekalian campuran dimana dalam membentuk Pemerintahan menggunakan sistem Parlementer dan dalam memilih Kepala Negara dengan sistem Presidensial, seperti yang diterapkan sejumlah negara a.l. Perancis dan Timor Letse.
Dengan didasari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara, arsitektur sistem kenegaraan termasuk eksistensi keberadaan seluruh lembaga demokrasi dan tata hubungannya, serta mekanisme politik yang ada perlu di “design” ulang. Sebaliknya, nilai-nilai luhur Pancasila dan nilai-nilai lainnya yang tertuang dalam Pembukaan harus dijabarkan dalam batang tubuh UUD. Dengan demikian nilai-nilai intrinsik yang terkandung didalamnya secara sempurna dijelmakan menjadi nilai-nilai operasional yang tertuang dalam batang tubuh UUD 1945, sehingga menjadi hukum positif yang mengikat semua pihak.
Dan kedepan tidak ada lagi nilai yang sumbernya dari import begitu saja diadopsi dan kemudian diberi cap Pancasila tak peduli isinya bertentangan dengan semangat, jiwa, kearifan dan adat istiadat serta budaya bangsa kita.
Dengan kata lain, kedepan sistem demokrasi kita sepenuhnya menggunakan cita rasa Indonesia. Sehingga dalam mengatur hak berserikat dan kebebasan menyampaikan pendapat umpamanya, kita tidak perlu memilih model Amerika atau Jerman. Karena, kita punya faham sendiri yang menempatkan kepentingan negara dan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan. Bagi kita norma tersebut sama sekali tidak merugikan kepentingan pribadi dan golongan yang manapun, karena keduanya melekat dalam kepentingan yang lebih besar, yaitu bangsa dan negara.
Sebagai masyarakat “arisan”, gotong royong, komunal, syariah, dan apapun sebutannya, maka dalam berdemokrasi kita tidak mungkin menerapkan norma mayoritas seperti yang dianut oleh negara-negara demokrasi yang berbasis pada konsep “nation state”. Hal ini terkait dengan realita, bahwa yang ada di kita baru sebatas keberadaan suku-suku bangsa, belum Indonesia sebagai bangsa.
Kedepan, nilai “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan” diwujudkan dalam bentuk proses musyawarah dalam pembikinan perundang-undangan, haruslah dilakukan oleh orang-orang ahli dibidangnya. Kita tidak boleh lagi menyerahkan penyusunan hal-hal prinsip kenegaraan seperti UU dan apalagi UUD kepada mereka yang bukan ahlinya, tak terkecuali kepada anggota DPR dan MPR sekalipun. Walapun untuk pengesahan tetap oleh lembaga demokrasi terkait, yaitu untuk UU oleh DPR dan untuk Amandemen UUD oleh MPR.
Begitu pula terhadap produk perundang-undangan yang dihasilkan, kedepan bicara UUD maupun UU bukanlah sekedar persoalan sah atau tidak sah secara yuridis formal, tapi amanat yang dikandungnya secara obyektif rasional harus dapat diuji kebenaran dan validitas keilmuannya.
Dengan demikian, makna kedaulatan rakyat yang diatur dalam UUD tidak terganjal atau terdistorsi dan apalagi ternegasikan justru oleh UU turunannya. Karena kedepan, anak bangsa siapapun ia tidak boleh jadi korban dan apalagi didholimi oleh negara atas nama hukum, seperti yang banyak terjadi selama ini.
*Mayor Jenderal TNI (Purn), Penulis Buku “Menata Ulang Sistem Demokrasi Dan TNI Menuju Peradaban Baru”, Terbitan Parrhesia, Tahun 2006.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});